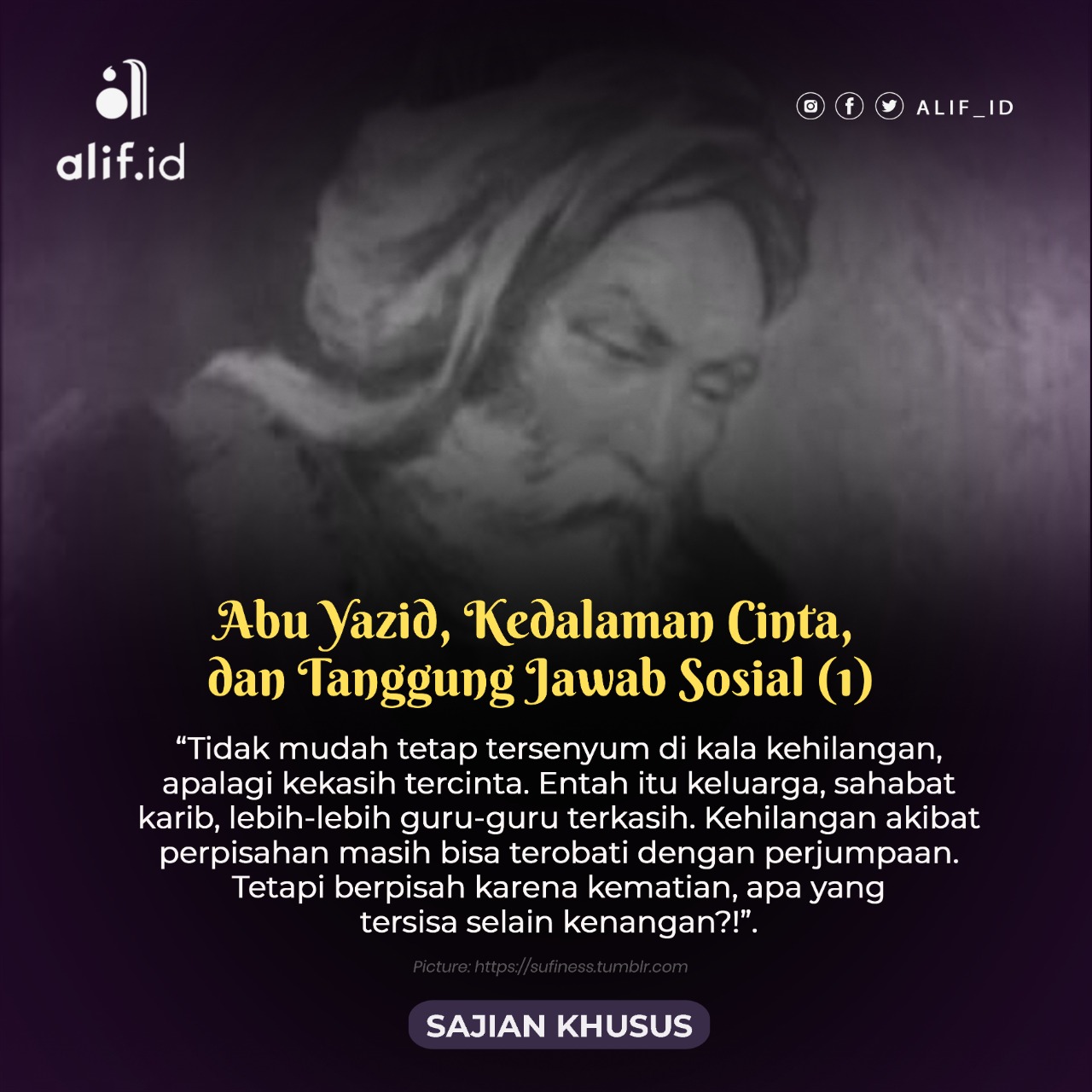
“Aku memasuki kota Tabaristan. Aku lihat arus-arus sungai mengalir deras lalu menyatu bersama samudera. Engkau menyuruhku menyelam di sana, dan kembali ke permukaan tanpa melihat satu makhluk pun,” -Abu Yazid al-Busthomi.
Tabaristan adalah satu wilayah di Iran, yang menjadi saksi bisu kewaliyan Abu Yazid Al-Busthomi. Suatu hari ada sahabat Abu Yazid berujar padanya: “sewaktu ada pemakaman orang meninggal di Tabaristan, aku melihatmu bersama Khidir as. Dia merangkul lehermu dan engkau menaruh tanganmu ke punggungnya. Ketika para peziarah pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa.” Abu Yazid menjawab, “segala yang engkau katakan itu benar-benar terjadi.”
Tidak ada keterangan lebih lanjut siapa nama tokoh yang dimakamkan, sampai-sampai didatangi oleh waliyullah sekaliber Abu Yazid Busthomi dan Nabi Khidir as. Namun begitu, Tabaristan memang kota yang melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Dalam Tarikh Tabaristan, Bahauddin Muhammad menyebutkan Tabaristan sebagai kota para raja, ulama, orang-orang zahid, ahli ma’rifat, bahkan ilmuan medis, astronomi, filosof, dan penyair.
Beberapa nama besar ilmuan dari Tabaristan antara lain: Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari; Fakhrul Islam Abdul Wahid bin Ismail yang bergeral Imam Syafi’i Ke-2; Abul Faraj Ali bin al-Husain, seorang linguis dan filsuf, yang menulis banyak karya: al-Bulghah min Mujmal al-Lughah, Nuzhah al-‘Uqul, al-Farq baina al-Mudzakkar wa al-Muannas, Miftah al-Thibb, al-Kalim al-Ruhaniyah fi Hikam al-Yunaniyah; Imam Abdul Qadir al-Jurjani; Syeikh Abu Turab; Syeikh Abu Nu’aim; dan banyak lainnya.
Kematian orang-orang mulia dan dimuliakan Allah, memang menyisakan kenangan yang mendalam. Amal jariyah yang mereka tinggalkan, termasuk karya-karya besar yang bermanfaat ratusan ribuan tahun bagi generasi penerus, patut ditiru, dilanjutkan, dan diamalkan. Pertanyaannya, di tahun penuh duka-cita seperti sekarang ini, saat ratusan ulama dan kiai kita telah berpulang ke sisi Tuhan, sanggupkah kita melanjutkan perjuangan mereka?
Abu Yazid pernah berujar: “laisa mitsli mitslun fis sama-I yujad, wa la li mitsli sifatn fil ardhi tu’raf”. Tidak ditemukan sekalipun di langit padananku. Tidak pula ada sifat sepertiku yang dapat ditemukan di muka bumi.” Artinya, jika seorang ulama telah meninggalkan dunia ini, maka seluruh ilmu yang dibawa pergi tidak tergantikan lagi.
Rasulullah saw juga bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hamba-Nya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, dan orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan,” (HR. Bukhari).
Sebagaimana Abu Yazid memasuki kota Tabaristan, lalu melihat sungai-sungai deras mengalir, menuju samudera, dan diperintahkan menyelam di samudera itu, maka tentu kita semua harus begitu hari ini. Kita harus segera menyingsingkan lengan baju menyelami samudera ilmu para ulama dan kiai yang telah meninggalkan kita untuk selamanya, dan menanti kita di surga kelak.
Namun sekali lagi, ketika Abu Yazid berhasil menyelami samudera, ia kembali ke permukaan tanpa melihat satu pun makhluk. Ia hanya melihat keagungan dan kebesaran Allah. Artinya, kita meneruskan jejak para ulama kiai bukan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi hanya mengejar kenikmatan duniawi.
Abu Yazid mengajarkan: “an-nafsu tanzhuru ilad dunnya, war ruhu tanzhuru ilal ‘uqba, wal ma’rifah tanzhuru ilal maula. Fa man ghalabat nafsuhu alaihi fahuwa minal halikin. Fa man ghalabat ruhuhu alaihi fahuwa minal mujtahidin. Wa man ghalabat ma’rifatuhu alaihi fahuwa minal muttaqin.”
Nafsu itu selalu memikirkan duniawi. Ruh itu memikirkan akhirat. Ma’rifat itu memikirkan Tuhan. Barang siapa didominasi nafsunya maka ia termasuk orang yang celaka. Barang siapa yang didominasi ruhnya maka ia termasuk golongan mujtahid. Dan orang yang didominasi oleh ma’rifatnya maka ia termasuk orang yang bertakwa.
Kecintaan berlebih pada duniawi inilah yang membuat mentalitas manusia rusak. Allah sudah mengingatkan: “tetapi kamu (orang-orang kafir) lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi,” (Qs. al-A’la: 16-17). Ini terbukti oleh realitas politik kita hari ini, dimana kecintaan berlebih pada kenikmatan duniawi melahirkan mental-mental koruptor. Lebih ironis bila mata kepala masyarakat melihat figur-figur publik-karismatik kita juga ikut-ikutan bermental koruptor. Lalu kemana dan pada siapa lagi publik akan mencari sandaran keteladanan?
Untuk menghindari kecintaan pada dunia, Abu Yazid sampai berdoa: “wadidtu annallaha ta’ala ja’alad dunya luqmatan wahidah, fa a’thaniha hatta anbudzaha baina yadai kalbin, hatta la yaghtarra bihil khalqu.” Saya berdoa Allah menjadikan dunia ini sebesar genggaman tangan, lalu menyerahkannya padaku, dan aku melemparkannya ke anjing, supaya makhluk manapun tidak tertipu oleh pernak-pernik duniawi.
Ketidakcintaan pada duniawi semacam ini menjadi salah satu pangkal epistemologis Abu Yazid al-Busthami memiliki hati yang penuh cinta pada semua makhluk; cinta spiritual, bahkan rela menanggung derita bahkan siksa semua makhluk Tuhan. “Aku ingin kiamat segera terjadi, lalu aku membuat tenda di atas neraka. Aku tahu neraka jahannam bila melihatku akan padam, dan aku akan menjadi rahmat bagi sekalian makhluk,” ujar Abu Yazid suatu ketika.
(bersambung)
Sumber:
Qasim Muhammad Abbas, Abu Yazid al-Bashthami, Damascus: Al-Mada, 2004.
Bahauddin Muhammad bin Hasan bin Isfandiar, Tarikh Tabaristan, terj. Ahmad Muhammad Nadi, Kairo: al-Majlis al-A’la li al-Tsaqafah, 2002.
https://alif.id/read/imam-nawawi/abu-yazid-kedalaman-cinta-dan-tanggung-jawab-sosial-2-b238991p/