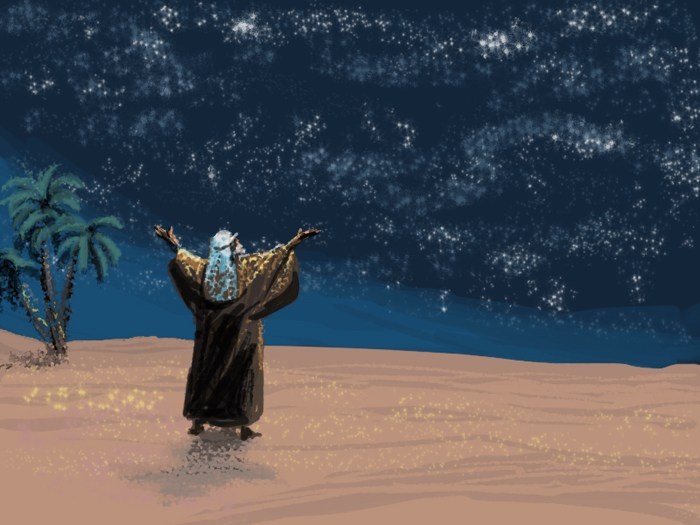
Barangkali, Ibrahim As. adalah Muslim pertama yang mempertautkan urusan penyakit dengan keimanan. Kala itu, ia sedang dalam konfrontasi dengan para penyembah berhala. Setelah menggugah mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kritis semisal “Apakah patung-patung itu mendengar seruan kalian?”, “Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi kalian?”, Ibrahim pun mulai mempromosikan Tuhannya. Dalam promosinya itu muncullah kata “sakit”. Tepat saat Ibrahim berkata, “Dan jika aku sakit, maka Dia-lah yang Menyembuhkan” (QS. Al-Syu’ra [26]: 80).
Jika diurai, proposisi kondisional yang digunakan Ibrahim di atas tersusun dari dua klausa. Klausa pertama berbunyi, “Jika aku sakit”. Sedang klausa kedua bunyinya, “Maka Dia-lah yang menyembuhkan.”. Pada klausa pertama, kata “sakit” dinisbatkan pada dirinya. Sementara dalam klausa kedua, kata “menyembuhkan” ia sandangkan kepada Tuhan. Secara sederhana, kita bisa menginterupsinya dengan sebuah pertanyaan. Bukankah sudah maklum bahwa penyakit dan kesembuhan sama-sama dari Tuhan, sehingga semestinya keduanya dinisbatkan pada subyek tunggal saja, yakni Allah Ta’ala?
Untuk menjawab kemusykilan ini para mufasir menawarkan beberapa kemungkinan. Ada yang menganggap bahwa penggunaan diksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk adab Ibrahim terhadap Tuhannya. Ibn Katsir, al-Qurthubi, dan al-Sam’ani adalah tiga dari sekian mufasir yang berpendapat demikian. “ Ulama telah sepakat bahwa yang
menyebabkan sakit dan yang menyembuhkan adalah Allah Swt. Lantas apa lagi maksud pilihan diksi itu kalau bukan karena adab?”, hujah al-Sam’ani dalam Tafsir al-Sam’ani.
Pendapat al-Nasafi tak jauh beda dengan yang sebelumnya. Dalam Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Takwil, ia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tak berkata, “Kalau Dia membuatku sakit”, lantaran secara utuh kalimat itu ia maksudkan sebagai bentuk ungkapan syukur. Dalam syukur, tidak wajar menisbatkan hal yang sifatnya mudarat pada Tuhan.
Pendapat ini memicu pertanyaan baru. Bila memang tak wajar menisbatkan hal-hal yang mudarat kepada Tuhan, bagaimana dengan kematian? Nyatanya, dalam ayat selanjutnya, Nabi Ibrahim justru secara eksplisit menisbatkan kata “mematikan” kepada Tuhan, dengan mengatakan “Dan Dia-lah yang mematikan kemudian menghidupkanku”, (Qs. Al-Syu’ara [26]: 81).
Di sinilah ulama memberi batasan bahwa agar bisa disebut mudarat (dlarar) suatu perkara haruslah bisa dirasakan. Berdasarkan teori ini, kematian tak memenuhi syarat untuk disebut mudarat lantaran ia tidak bisa dirasa. Beda halnya dengan sakit. Jika ada yang bilang bahwa mati itu menyakitkan, barangkali yang dimaksud bukanlah kematian itu sendiri, melainkan sakratulmaut atau penyakit yang mengantarkan pada kematian.
Ditambah lagi ada semacam kredo bahwa bagi jiwa-jiwa yang telah purna ilmu dan akhlaknya, menyatu dengan jasad adalah penderitan semata. Sedangkan berpisah darinya-yang itu berarti mati-adalah sumber kebahagiaan. Walhasil, sah-sah saja verba “mematikan” dinisbatkan kepada Tuhan. Sebab sekali lagi, kematian bukanlah mudarat.
Sementara itu, al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib juga menawarkan beberapa sudut pandang. Salah satunya, karena pada galIbn ya penyakit itu timbul akibat kecerobohan manusia dalam hal mengonsumsi makanan atau minuman dan lain sebagainya.
Dengan merujuk beberapa penafsiran tersebut, sama sekali tak ada kesan bahwa pernyataan Ibrahim di atas menjustifikasi arogansi semisal penolakan frontal terhadap tindakan-tindakan medis. Alih-alih mendukung, ayat tersebut justru menjelaskan bahwa penyakit seringkali adalah akibat kesembronoan pola hidup kita. Sebagaimana banyak bencana di luar tubuh manusia juga terjadi akibat ulah manusia.
Hal ini selaras dengan tesis dari dunia kesehatan yang menyatakan bahwa pola hidup seseorang nyaris selalu berbanding lurus dengan kualitas kesehatannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik adalah faktor utama resiko kesehatan global. Disebutkan pula bahwa merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik merupakan perilaku yang menjadi faktor risiko utama yang juga identik dengan penyakit-penyakit kronis seperti kardiovaskuler, kanker, penyakit pernapasan, dan diabetes.
Paduan antara ayat Allah yang terkatakan melalui lisan Ibrahim dan ayat-Nya yang tersirat berupa temuan-temuan dari dunia medis mengukuhkan betapa sejatinya sakit yang diderita menuntut tanggung jawab. Sesiap mungkin deritanya kita tanggung. Ihwal apa penyebabnya, bagaimana metode pengobatannya, sebisa mungkin kita jawab. Barulah urusan kesembuhan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Sebab hanya Dia-lah yang punya otoritas mutlak atas kesembuhan.
Pandangan semacam ini mesti terus ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di masa krisis kesehatan seperti sekarang. Lebih-lebih hasil penelitian terhadap konsepsi sosio-kultural suatu masyarakat di Jawa Timur menunjukkan bahwa pengetahuan dan pandangan yang salah tentang sakit, penyakit, dan kesehatan membentuk pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya, persepsi yang keliru dalam memandang penyakit berikut hal-hal yang bertautan dengannya menjadi batu sandung pertama dalam membangun masyarakat yang sehat. Boleh dikata bahwa konsepsi yang tidak adil terhadap penyakit adalah penyakit pertama yang mesti segera diobati.
Dengan menisbatkan sakit pada dirinya sendiri, Bapak dari agama-agama besar di muka bumi ini tengah meneladankan kejujuran dan keberanian untuk melakukan semacam rekognisi atas kealpaan merawat karunia Tuhan berupa kesehatan. Dan bukan justru ujug–ujug melimpahkannya pada Tuhan. Barangkali memang seharusnya Tuhan kita libatkan dalam segala urusan. Namun jika yang dimaksud adalah agar Tuhan bertanggung jawab atas keteledoran kita, tidakkah itu merupakan bentuk perselingkuhan yang liat antara kedurhakaan dan kepengecutan?
https://alif.id/read/sr/bagaimana-nabi-ibrahim-memaknai-sakit-b242893p/