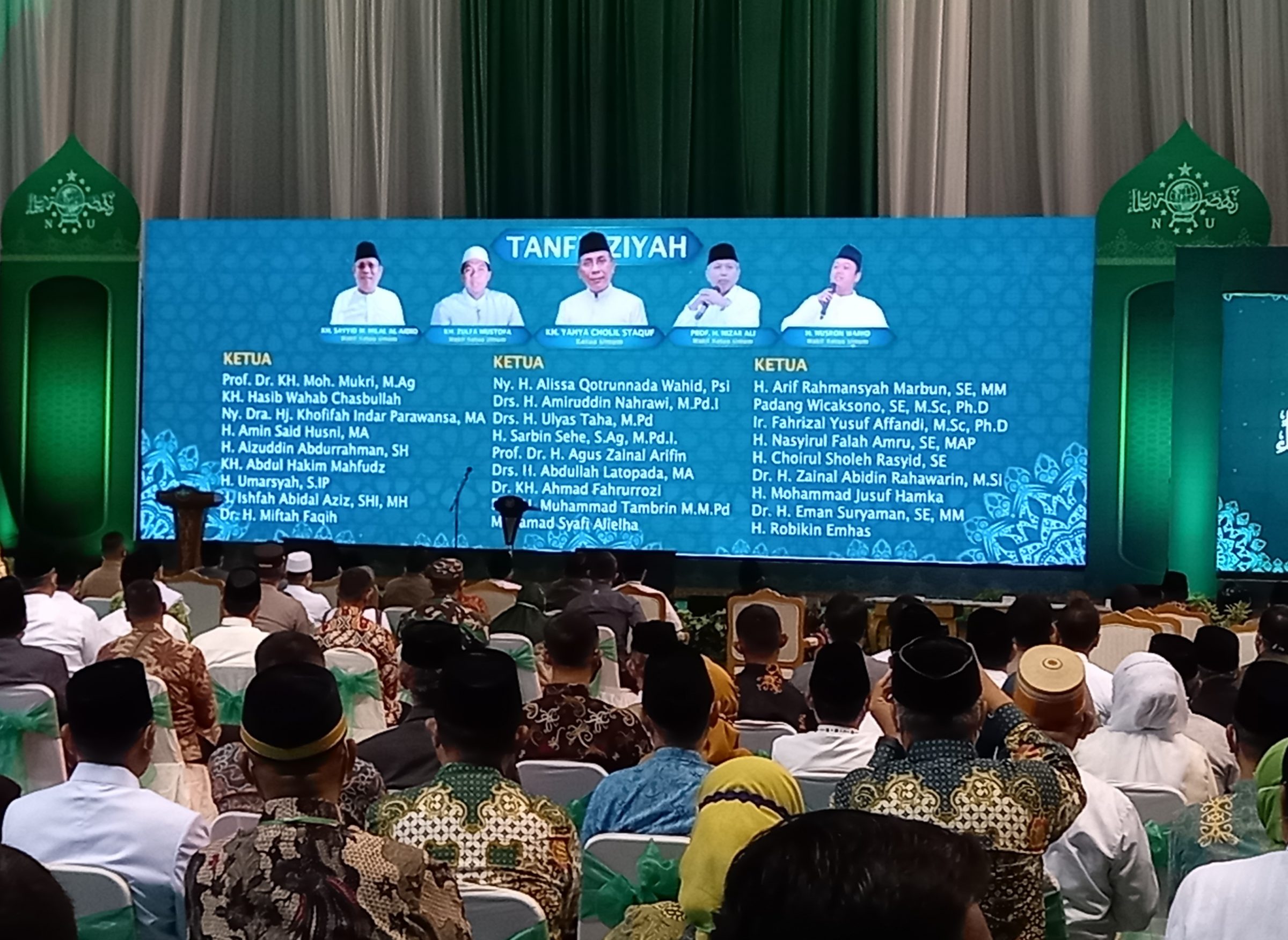
Indonesia sangat beruntung sekali memiliki dua ormas Islam terbesar. Beruntung karena memiliki Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy’ari tahun 1926 dan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912. Sampai saat ini masih banyak orang yang bertanya-tanya, apa perbedaan diantara NU dan Muhammadiyah.
Yang jelas, perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah hanya pada aspek furu’ al-din (hal yang partikural dalam Islam). Sementara yang menyangkut masalah ushul al-din (hal pokok dalam Islam) tidak ada perbedaan diantara keduanya.
“Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua,” jelas Kiai Zulfa.
“Saudara tua!,” memastikan Najwa Shihab.
“Iya,” timpal Kiai Zulfa.
Sementara itu Prof Mukti pada saat gilirannya menjawab, beliau mengatakan:
“Kalau NU itu adik bongsor. Karena usianya 14 tahun lebih mudah, tapi anggotanya lebih banyak dari pada muhammadiyah.” Jelasnya kepada Najwa.
“Saya kira termasuk Mahasiswa UMS, ini mayoritas adalah dari NU.” Imbuhnya.
Sebenarnya, secara nasab keilmuan, keduanya (Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan) sama-sama pernah nyantri kepada Syaikhona Kholil al-Bangkalan. Singkat cerita, usai di Bangkalan, keduanya melanjutkan study ke Semarang di bawah asuhan Kiai Sholeh Darat. Kiai Sholeh Darat adalah ulama terkemuka, ahli nahwu, tafsir, juga ahli ilmu falak.
Kepada Kiai Sholeh Darat, Hasyim dan Darwis (berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, tabarruk dengan gurunya Syekh Ahmad Zaini bin Dahlan, Mufti Syafi’iyah di Tanah Haram) belajar tekun dan rajin. Hingga akhirnya oleh Kiai Sholeh keduanya diperintahkan untuk melanjutkan study di Makkatul Mukarramah.
Setibanya di Makkah, keduanya menjadi murid kesayangan Imam Masjidil Haram yakni, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Dari sinilah perbedaan keduanya mulai tampak. Kecenderungan Kiai Hasyim pada Hadits, sementara Kiai Dahlan lebih tertarik pada bahasan pemikiran dan gerakan-gerakan Islam.
Menariknya, ketika terjadi gesekan antara anggota Muhammadiyah dengan kalangan pesantren, Kiai Hasyim turun tangan dan berkata: “Kita dan Muhammadiyah sama. Kita Taqlid Qauli (mengambil pendapat ulama salaf, mereka Taqlid Manhaji (mengambil metode).”
Itu artinya, perbedaan-perbedaan partikural di dalam Islam (NU dan Muhammadiyah) tentu saja tidak boleh diperpanjang. Sebab, sesuatu yang partikural memang tidak bisa dikonsensuskan (ijma’). Misalnya, apakah berkunut dan tidak saat melaksanakan shalat subuh, tentu tak bisa dikonsensuskan. Alih-alih konsensus, sudah pasti diperselisihkan sepanjang zaman dan sepanjang umat Islam berada dipermukaan bumi ini.
Kiai Hasyim Muzadi dalam suatu kesempatan (cerita NU dan Muhammadiyah) pernah menyampaikan, “bahwa antara NU dan Muhammadiyah selisih sedikit saja ribut. Yang satu qunut dan satunya tidak. Padahal, sebetulnya di kitabnya orang NU ada qunutnya dan ada yang tidak qunutnya. Akan tetapi, karena dia terkooptasi oleh perkembangan akhirnya terjadilah keributan.”
Meski demikian, kedua ormas ini cukup mencerminkan perbedaan-perbedaan secara tradisi, cara berpikir, bahkan perbedaan didalam menafsirkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Perbedaan cara menafsirkan tetap diperbolehkan sejauh perbedaan itu sama sekali tidak menyentuh esensi pokok dalam agama Islam.
Sekurang-kurangnya, pandangan ini didasarkan pada pendapat Imam at-Taftazani dalam kitab Hasyiyah al-Athar mengatakan: لا يمس لب العقيده “tidak menyentuh akidah”, bahwa perbedaan-perbedaan dikalangan umat Islam ketika tak menyentuh esensi pokok akidah, maka perbedaan itu adalah rahmat bagi seluruh umat Islam.
Pada dasarnya Muhammadiyah memang tidak bermazhab (Muhammadiyah tidak seperti NU dalam bermazhab, misalnya NU punyak mazhab akidah, fikih, tasawuf), dalam hal ini menggunakan “Manhaj Tarjih Muhammadiyah”. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih yang berbunyi: “Tidak mengikat diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.”
Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mengharuskan diri bermazhab. Kita tahu bahwa, NU dalam tiga dimensinya memiliki mazhabnya masing-masing. Dalam akidah ada Al-Asy’ari dan Al-Maturidi, di fikih ada mazhab yang empat (Hambali, Maliki, Syafi’i dan Hanafi). Sementara dalam tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaid al-Baghdadi.
Jika ada empat mazhab kenapa harus Syafi’i?
Mafhum, kalangan NU lebih cenderung pada mazhab Syafi’iyah. Ini terlihat dalam penerapan ushul fikih-nya Imam Syafi’i yang sampai detik ini tetap dioperasikan oleh kiai-kiai NU dalam pengambilan hukum atas suatu persoalan yang terjadi. Bahkan, keputusan-keputusan hukum terdahulu yang dilakukan oleh Imam Syafi’i, sampai saat ini masih diadopsi dan menjadi tradisi yang kuat dikalangan NU, pasantren khususnya.
Karena itu, untuk melihat kerangka utuh fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi’i, kita bisa melihat salah satu kitabnya yang termasyhur bertajuk kitab Ar-Risalah. Melalui kitab ini, Imam Syafi’i kemudian populer dalam khazanah fikih dan ushul fikih. Bagaimana tidak, seluruh ide Imam Syafi’i tentang ushul fikih-nya terdokumentasikan detail dalam kitab tersebut. Tak mengherankan jika para pemikir (Barat dan Timur) mengatakan bahwa Imam Syafi’I lah pencetus lahirnya kaidah-kaidah ushul fikih dalam dunia Islam.
Masih tentang as-Syafi’i. Dominannya NU pada mazhab Syafi’i ini bukanlah tanpa sebuah alasan. Alasan tersebut dapat kita pahami bahwa Imam Syafi’i adalah tokoh fikih yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Ia adalah murid senior dari tokoh fikih yang termasyhur dizamannya, yaitu: Imam Malik dan Abu Hanifah.
Dari kedua guru inilah, Imam Syafi’i berhasil menciptakan nalar fikih. Nalar fikih yang dimaksud adalah memadukan dua epistemologi sekaligus, antara metodologi ahl al-hadits dan ahl ar-ra’yi. Dua paduan epistemologi fikih inilah juga yang menjadikan alasan paling kuat mengapa para kiai-kiai NU banyak mengadopsi fikih-nya Imam Syafi’i.
Terlepas dari itu semua, hakikatnya dalam bermazhab, kita hanya mengambil satu dari empat (qauli dan manhaji), yang kalau ditelusuri rumpun dan genealoginya adalah sama. Sebut saja Imam Ahmad bin Hambal yang berguru kepada Imam Syafi’i, Imam Syafi’i berguru pada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah meski secara tidak secara langsung, tapi melalui muridnya yaitu, Hasan as-Syaibani (orang gemuk dengan kepala botak,tapi alimnya luar biasa).
Semuanya, jika ditelusuri maka akan berpuncak kepada Jakfar as-Shadiq. Ia adalah salah satu rujukan utama dalam mursyid tariqah-tariqah muktabarah yang dianut di lingkungan Nadhlatul Ulama. Demikian. Hal ini perlu sekali untuk di jelaskan ditengah kecenderungan orang yang acap kali secara membabi-buta membeda-bedakan mazhab.
Sekali lagi perlu, karena seseorang seringkali membedakan mazhab yang seakan mereka dari golongan yang lain bukan dari rumpun yang sama. Itu artinya, jika belakangan ada orang berkata, kita harus kembali pada manhajnya ulama salaf, maka pertanyaannya adalah manhajnya siapa? Karena dikalangan para sahabat sendiri terjadi perbedaan pendapat didalam memahami hadits.
Sebuah Catatan
Jakfar as-Shadiq adalah anak dari Muhammad al-Bakir. Muhammad al-Bakir anak dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak dari Husein bin Ali bin Abi Thalib. Jakfar as-Shadiq mempunyai seorang ibu bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah mempunyaki bapak bernama Qasim. Qasim mempunyai bapak namanya Muhammad bin Abi Bakr as-shiddiq. Muhammad bin Abi Bakr as-shiddiq mempunyai ibu namanya Asma binti Umaits.
Asma binti Umaits inilah mantan istri dari Jakfar bin abi Thalib. Kita tahu, Jakfar bin abi Thalib adalah saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib yang meninggal didalam peperangan muktam (meninggalkan empat orang anak). Akhirnya, pasca meninggal dinikahi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu memiliki anak bernama Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar mempunyai anak Qasim, dan Qasim punyak anak bernama Fatimah (ibu dari Jakfar shadiq). Wallahu a’lam bisshawab.
https://alif.id/read/safa/catatan-penting-menyambut-1-abad-nu-antara-mazhab-dan-manhaj-b247051p/