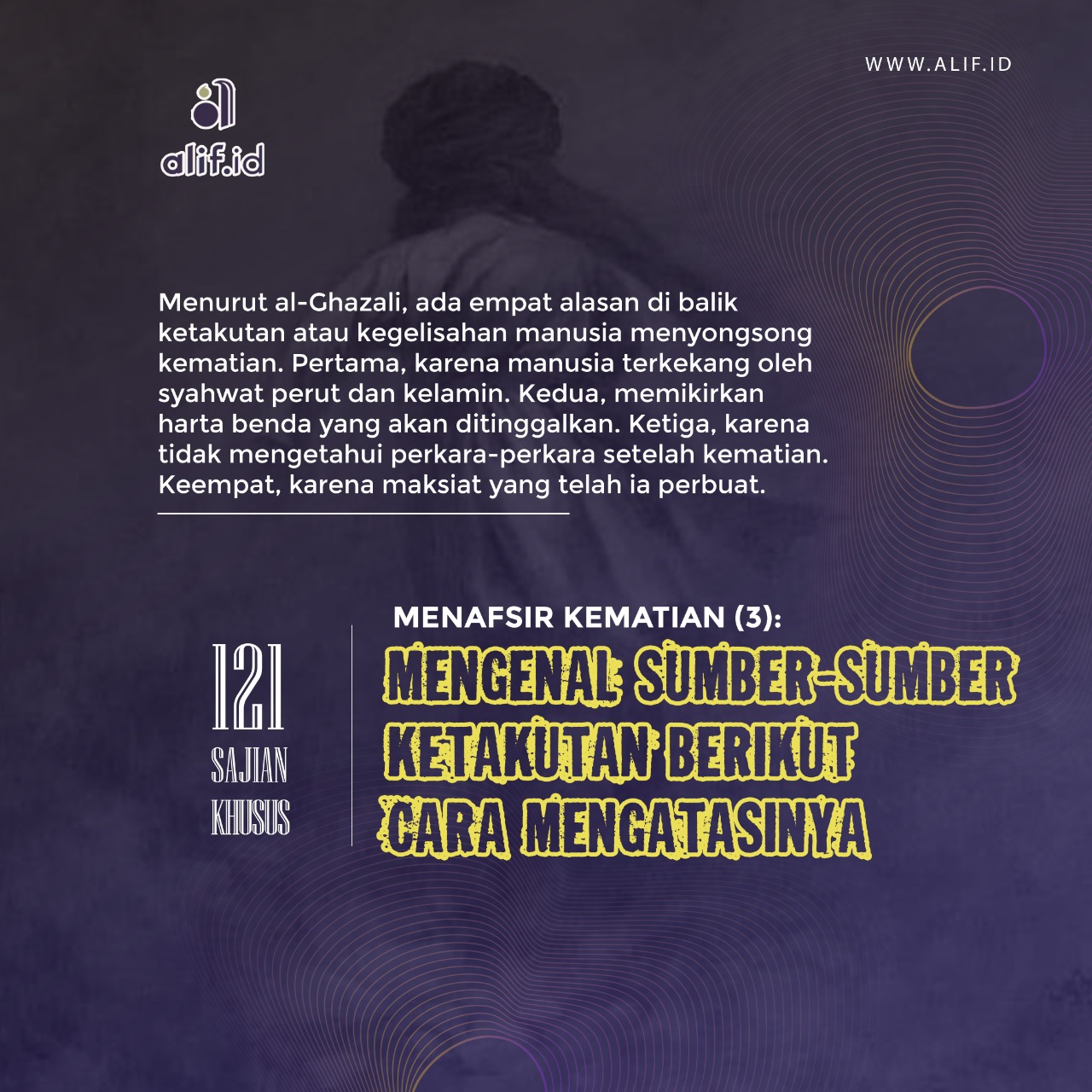
Rasa takut menghadapi kematian amatlah kompleks. Namun bila sederhanakan, ketakakutan itu dapat dipetakan menjadi dua macam. Pertama ketakutan objektif, yakni ketakutan yang benar-benar berasal dari kematian itu sendiri. Misalnya, kita pandang kematian sebagai petaka, penderitaan, kebinasaan, dan seterusnya. Dengan alasan-alasan itu, kemudian kita menjadi takut dan menolak kematian. Kedua, ketakutan subjektif yang berasal dari hal-hal yang berada di luar kematian. Artinya yang ditakuti bukanlah kematian itu sendiri, melainkan hal-hal yang mengiringinya. Contohnya, orang takut mati karena kematian menjadi ajang perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya, dan seterusnya.
Hubungan keduanya memang tak saling meniscayakan. Artinya seseorang bisa saja takut mati murni karena kematian itu sendiri. Boleh jadi sebenarnya yang ia takutkan bukan kematiannya, melainkan ekses-ekses yang ditimbulkan kematian seperti telah dicontohkan di atas. Tetapi juga bukan mustahil, kedua-duanya dapat hadir secara serentak dalam benak seseorang. Bukan tak mungkin seseorang takut mati karena ia anggap mati itu menyakitkan, sekaligus karena ia enggan meninggalkan karirnya yang sedang gemilang. Pada titik ini intesitas ketakutan akan meningkat.
Ketakutan jenis kedua inilah yang al-Ghazali paparkan dalam Mizan al-‘Amal. Menariknya, di awal pembahasan bertajuk, “Bayan Nafy al-Khauf min al-Maut”, al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa ketakutan-ketakutan itu tidak bersumber dari akal sehat. Dengan kata lain, orang yang memaksimalkan potensi akalnya tidak akan terjebak oleh ketakutan macam itu.
Menurut al-Ghazali, ada empat alasan di balik ketakutan atau kegelisahan manusia menyongsong kematian. Pertama, karena manusia terkekang oleh syahwat perut dan kelamin. Dari zaman Nabi Adam, sejarah mencatat bahwa syahwat perut dapat dibilang paling sering menjerumuskan manusia ke jurang kebinasaan. Tak heran, dalam Ihya ‘Ulum al-Din, al-Ghazali mengungkapkan bahwa syahwat perut adalah a’dham al-muhlikat li ibn Adam, hal yang paling merusak bagi umat manusia. Gara-gara syahwat ini, Nabi Adam dan Siti hawa dideportasi dari surga. Selanjutnya, syahwat perut juga mendorong bangkitnya syahwat kelamin. Kolaborasi epik antara dua syahwat ini akhirnya mengundang kecintaan pada harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya.
Dengan tibanya kematian, kesempatan untuk menyalurkan dua syahwat ini pun otomatis sirna. Sebab sebagaimana disinggung dalam tulisan terdahulu, salah satu fungsi kematian adalah memutus segala keinginan duniawi, hadim al-ladz-dzat. Walhasil kematian diniliai sebagai ancaman laten bagi keinginan-keinginan ini. Manusia yang menolak mati dengan alasan ini, kata al-Ghazali, ibarat seseorang ingin menolak penyakit dengan penyakit. Itulah yang disebut al-Ghazali sebagai ‘ain al-raqa’ah, yakni inti ketololan plus tak punya malu.
Kedua, memikirkan harta benda yang akan ditinggalkan. Dengan kematian, harta yang telah susah payah dikumpulkan mau tak mau harus ditinggalkan. Tak pelak, kematian dianggap sebagai pemisah antara manusia dengan hartanya yang kerap menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan. Di sini pula sering terjadi mispersepsi dalam memandang hakikat dunia, harta benda, dan kepemilikan.
Tak bisa dimungkiri, bagi sementara orang, fasilitas duniawi berupa harta benda dinilai abadi dan menjanjikan kebahagiaan tak terperi. Padahal, jika dibanding kebahagian ukhrawi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, segalanya tak ada artinya apa-apa. Pun benda-benda itu kerap distempel sebagai hak milik secara mutlak. Padahal semuanya adalah titipan, sebab Pemilik yang mutlak nan hakiki hanya Allah semata. Itulah mengapa ketika semua itu direnggut kembali oleh Sang Maha Pemilik, kita dianjurkan ber-istirja’, mengakui bahwa semua itu hanya milik Allah dan hanya kepada-Nya semua akan kembali.
Ketiga, karena tidak mengetahui perkara-perkara setelah kematian. Kematian seakan lorong gelap, tanpa lentera, tanpa rambu dan batas-batas. Terlebih, di hadapan kematian, kita adalah orang asing. Maka ia butuh lentera, butuh peta, butuh tuntunan agar ia bisa selamat sampai tujuan. Karenanya, mau tak mau untuk mengatasinya kita harus mempelajari ilmu yang membahas fase-fase manusia setelah kematian. Termasuk memepelajari hakikat ruh, hubungan ruh dengan badan, keistimewaannya, tujuan diciptakannya, ke mana ia akan berpulang, dan seterusnya. Di sinilah mempelajari psikologi dan eskatologi tak kalah penting dengan dengan mempelajari ilmu sosial maupun ilmu alam. Sebagaimana telah diwant-wanti oleh syariat dalam banyak tempat.
Keempat, karena maksiat yang telah ia perbuat. Ia takut akan ancaman yang dijanjikan baginya semenjak dan setelah kematian itu berlangusng. Solusinya jelas bukan dengan bersedih. Melainkan dengan memberdayakan ketakutan menjadi pendorong untuk segera bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ketakutan ini mesti menjadi momentum untuk memparbaiki kesalahan, menambal kekurangan-kekurangan yang telah banyak dilakukan. Dalam keadaan ini, bersedih dan tak berupaya mengejar ketertinggalan tak ubahnya merobek pembulu darah, sedangkan darah telah mengalir. Nyatanya, ia hanya duduk mengaduh, mengeluhkan lukanya. Padahal, ia mampu membalutnya. Kata al-Ghazali tegas, ini pula termasuk kebodohan.
Empat hal tadi dapat membantu kita mendiagnosis ketakukan-ketakutan yang bersarang dalam diri. Upaya ini tak lain adalah langkah awal dalam menyambut kematian dengan hangat. Intinya inti, untuk menyongsong kematian diperlukan seperangkat pengetahuan, bukan ratapan kesedihan. Ngomong-ngomong, menurut Anda, sebagian orang yang takut mati dengan alasan masih jomblo atau belum menikah masuk kategori yang mana?