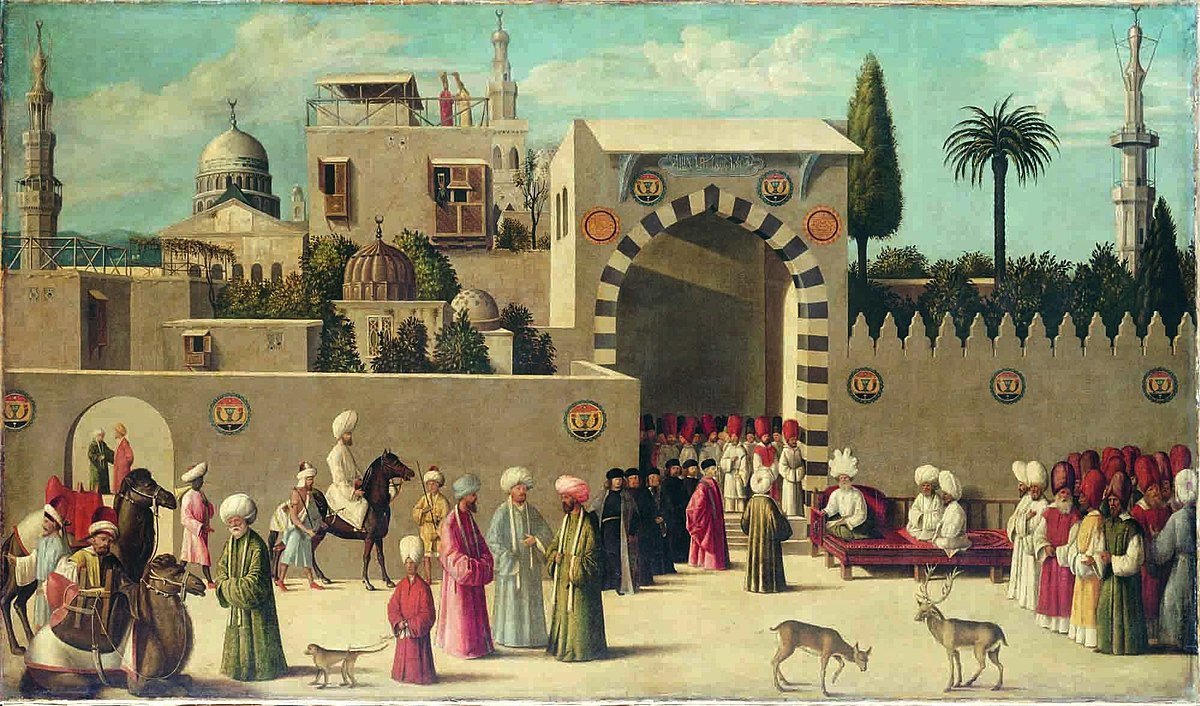
Selain mengkritik Islam, ada satu hal yang juga gamang untuk disentuh oleh sebagian besar umat muslim. Anda sudah bisa menebak apa itu, tidak lain adalah ijtihad. Sejak semula memang diletakkan sebagai sesuatu konsep yang luar biasa agung dan tidak boleh disentuh sembarang orang. untuk melihat keagungan ijtihad ini sendiri kita bisa melacak satu riwayat yang masyhur. Bahwa jika seseorang berijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapat dua pahala, jika salah satu pahala. Ini menunjukkan betapa posisi ijtihad—selain juga urgen—punya strata yang tinggi di dalam tubuh agama Islam.
Islam seringkali diidentifikasi dengan fikih (dalam arti yang dipakai saat ini), hukum Islam, atau Islamic law. Sementara fikih sendiri tidaklah kemudian bisa terwujud tanpa adanya jalan ijtihad. Dari inilah kemudian ijtihad mendapat posisi spesial. Bukti lain untuk mengukuhkan bahwa ia spesial karena penerapan syarat yang ketat. Untuk hal ini mungkin bisa dirundingkan lebih lanjut, apakah ia tetap diperketat atau harus diberi kelonggaran. Yang jelas keistimewaan dari ijtihad itu selain berlandaskan doktrin teologis juga dibungkus oleh beberapa pendapat ulama terdahulu yang mengukuhkan keistimewaannya.
Di saat yang sama inilah, ketika ijtihad menjadi barang antik dan hanya bisa disentuh kalangan elit (seseorang yang dijustifikasi paling pakar dala urusan agama), budaya taklid menjamur. Seseorang hanya mencukupkan untuk mengikuti apa yang telah menjadi pendapat dari orang-orang sebelumnya. Dalam status keikutsertaan, strata taklid berada di derajat paling bawah. Ia memang sengaja didesain bagi masyarakat yang dianggap tidak punya kompetensi untuk melakukan ijtihad. Barangkali ini adalah hal paling nyaman yang tidak disadari oleh banyak orang secara langsung.
Kementakan ijtihad seolah-olah tertutup dan hanya dicukupkan untuk bertaklid buta. Pada puncaknya yang paling ekstrem, itu berimplikasi pada usaha menjunjung tinggi pendapat yang diikuti sembari menegasi pendapat lain yang dianggap tidak sejalan. Dampaknya, hukum Islam atau fikih mengalami ketertutupan dan hanya dicukupkan pada satu pendapat. Padahal, diakui atau tidak, yang tidak bisa dihilangkan dari fikih adalah budaya ikhtilaf. Sedangkan budaya taklid mencoba menegasi ikhtilaf itu sendiri dan menjunjung tinggi barisannya sendiri.
Jika hendak ditarik ke titik historis, hal ini bisa dimulai ketika fikih masuk ke fase kemunduran. Dalam istilah yang digunakan oleh Mun’im Sirry fase keterpakuan tekstual. Tidak bisa ditolak bahwa hal tersebut punya kelinda erat dengan diktum ‘pintu ijtihad telah tertutup’. Semula hal ini dipicu oleh kondisi sosial-politik yang membuat beberapa kalangan menyandingkan fikih terlalu dekat dengan kepentingan, baik pribadi maupun kolektif. Sehingga, kesimpulan-kesimpulan hukum yang dihasilaknnya justru tidak lebih dari sekadar legimitasi atas kepentingan itu.
Faktor yang lain yang cukup punya kekuatan untuk menjermuskan umat muslim ke zona taklid adalah kekaguman berlebihan terhadap para ulama sebelumnya. Perlu dipertegas bahwa di sini tidak melarang siapapun kagum terhadap kecemerlangan yang dicapai waktu itu. Namun, ketika kekaguman membawa dampak negatif dan menjadikan umat yang lahir belakangan merasa inferior, maka hal tersebut perlu ditepis. Kodifikasi fikih imam mazhab juga banyak memberi pengaruh, karena dengan gampang umat yang lahir belakangan akan merujuk terhadap kodifikasi itu.
Ditambah lagi banyaknya orang yang tidak punya kompetensi yang turut serta mengeluarkan fatwa. Jabatan mufti pada masa itu dipegang oleh orang yang justru membelokkan tujuan fatwa. Sebagian besar juga mengincar jabatan kadi (qadhi) yang mencari perantara lewat fikih itu sendiri. Mereka tidak punya keahlian ilmiah yang memadai dan hanya mencukupkan diri menghafal hukum dan preseden mazhab terdahulu yang menjadi pegangan di peradilan. Mereka hanya mengikuti apa yang ditetap oleh ulama sebelumnya tanpa melakukan pergelutan ilmiah. Terdistorsinya realita sedemikian rupa dan kompleks memantik fukaha untuk mengeluarkan seruan pintu ijtihad telah tertutup [Mun’im A. Sirry, 1995:130].
Pertanyaannya, untuk hari ini apakah masih mungkin untuk melakukan ijtihad? Tentu jawabannya mau tidak mau harus menganggukkan kepala. Beberapa landasan yang cukup kuat bisa didiskusikan lebih detail lagi. Setidaknya, realita yang kita hadapi menuntuk seseorang yang memang punya kepakaran khusus di bidang hukum Islam untuk kreatif. Dalam arti, mesti selalu cekatan melihat tiap fenomena sosial yang mengitari dan kemudian mencari solusinya lewat pintu ijtihad. Hal ini tentu tidak bisa langsung diterpakan, terlebih dahulu kita merubah diktum ‘pintu ijtihad dibuka kembali’.
Kita selanjutnya bisa merundingkan terkait dengan syarat ijtihad yang dinilai berat. Kita bisa menyederhanakannya tanpa harus membuat umat merasa kesulitan sampai pada taraf mujtahid. Kalaupun tidak hendak direduksi, solusi terbaiknya yang bisa dilakukan adalah ijtihad kolektif. Ijtihad model ini tidak meniscayakan monopoli individu, melain oleh sekelompok orang yang memang kompeten di bidang masing-masing. Ijtihad dapat dilakukan melalui cara dan pendekatan kompetensi tiap orang tersebut.
Semisal yang pakar Al-Qur’an melihat sebuah problem dari kacamata Al-Qur’an, begitu pula yang hadits, dan seterusnya. Dan konklusinya, menyudahi dan melahirkan sebuah kesimpulan yang bertemu di satu titik yang sama dari semua pendekatan tersebut. Inilah keterbukaan untuk melakukan pengkajian dan ijtihad kembali di zaman yang jaraknya dengan nabi sangat jauh. Kita hanya perlu meyakini bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka, kembali dibuka, dan tidak akan pernah tertutup lagi.
https://alif.id/read/rofqil/menyoal-kemungkinan-ijtihad-b245642p/