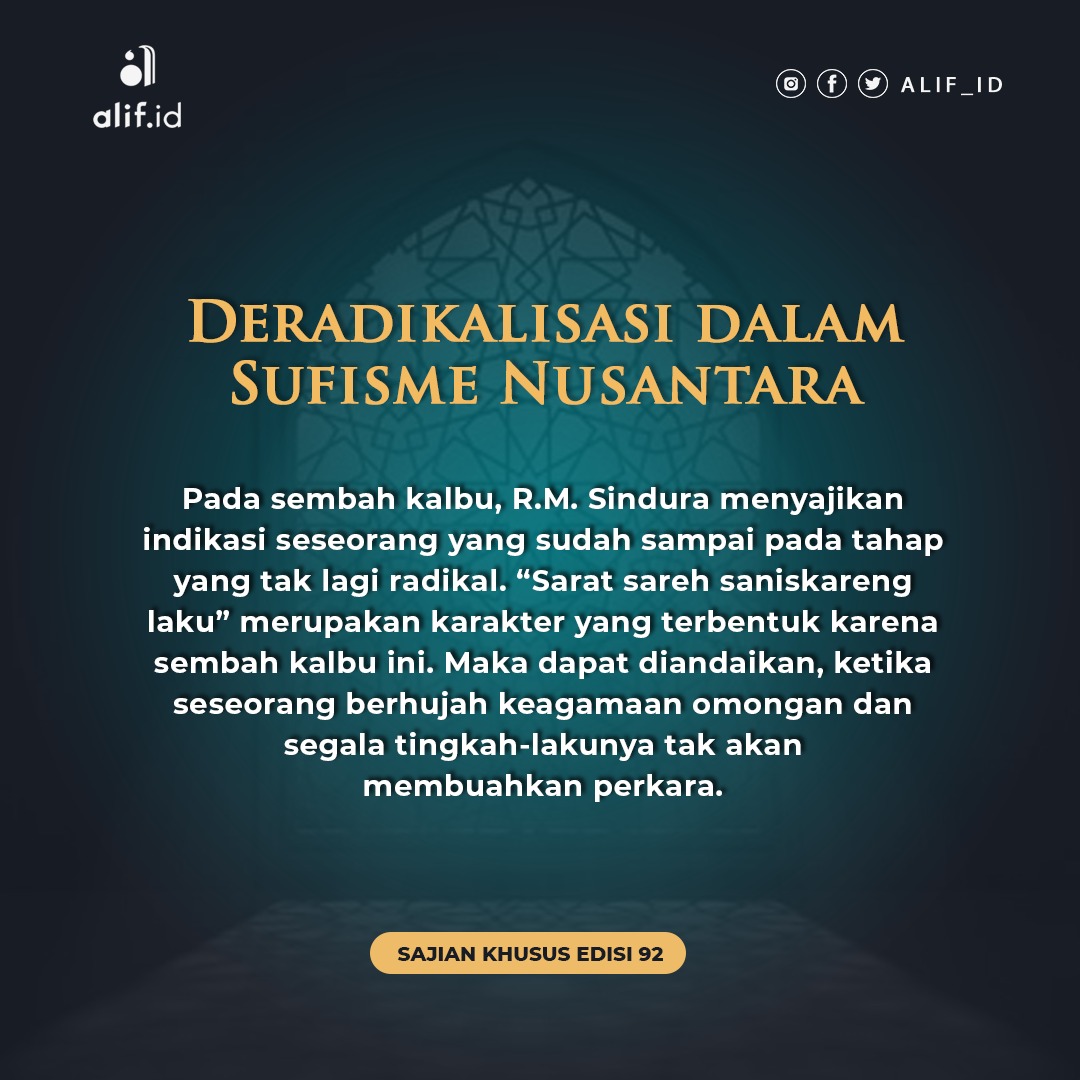
Radikalisme tak ayal lagi adalah pola pemahaman dan pola penyikapan yang bertentangan dengan konsep budi pekerti atau akhlaq tersebut. Ketika kita berkesimpulan demikian, maka radikalisme—yang dalam konteks Indonesia selalu dilekatkan dengan klaim agama Islam—adalah sangat bertentangan dengan semangat dan jejer Nabi Muhammad yang ironisnya sering dianggap sebagai “pendiri” agama Islam.
Seandainya Sunan Bagus mengetengahkan deradikalisasi dengan jalan menyelaraskan pola pemahaman dan pola sikap yang direpresentasikan dengan dedahannya atas seorang guru yang baik dan tutug, maka R.M. Sindura atau Mangkunegara IV mengetengahkan sebuah praktik atau laku yang perlu ditempuh untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan diri. Sangat wijang bahwa dalam hal ini R.M. Sindura cukup terpengaruh oleh ‘Ajaibul Qulub-nya al-Ghazali. Laku itu disebutnya dengan istilah “sembah catur” yang meliputi sembah raga, sembah kalbu, sembah jiwa, dan sembah rasa.
Dalam agama Islam terdapat ayat yang menegaskan bahwa shalat konon dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang shalatnya seakan tertib sementara fitnah, perendahan, perbuatan keji dan radikalitas (munkar) lainnya tetap berjalan? Pada titik inilah Mangkunegara IV mengetengah indikasi laku sebuah ilmu yang berhasil atau tak sekedar lamisan atau umuk doang.
Laku itu semestinya tak hanya berhenti pada tataran raga yang ternyata tak menjamin perubahan apa-apa pada diri. Ketika kita menyempatkan diri melihat kehidupan keagamaan orang-orang yang ditengarai radikal, tampak bahwa mereka masih terlihat dapat di-kendhangi laiknya penari ronggeng—alias belum tutug sebagaimana kriteria seorang guru dari Sunan Bagus. Isi-isi hati mereka masih menyembul laiknya kijang, ular ataupun gajah bahkan ketika mereka tengah beragama sekalipun. Di balik gayanya yang penuh nuansa keagamaan, ternyata kesadaran panggung masih menjadi karakteristik utama mereka.
Menurut R.M. Sudira, ukuran kealiman bukanlah terletak pada seberapa pandai atau seberapa mendalam penguasaan ilmu-ilmu agama seseorang, tapi pada kemampuannya dalam menyingkirkan potensi radikalitasnya sendiri (dur angkara). Karena itulah sang adipati yang sangat terpengaruh oleh al-Ghazali ini meletakkan laku dan kesentosaan diri sebagai indikasi kealiman seseorang.
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara
Semestinya, menurut R.M. Sindura, mereka itu beranjak lebih jauh lagi untuk tak semata raganya saja yang terkesan beragama. Mereka mesti pula menginjak pada sembah cipta atau sembah kalbu dimana laku-nya “amung nyenyuda ardaning kalbu/ pambukaning tata titi ngati-ati/ atetep talaten atul/ tuladan marang waspaos.”
Berdasarkan dedahan Mangkunegara IV, pada dasarnya orang-orang yang radikal identik dengan orang-orang yang sedang sakit hati. Sebab menurut al-Ghazali, yang sudah dikontekstualisasikan dengan budaya Jawa oleh Mangkunegara IV, iren-dahwen-panasten-srei-drengki-ujub-riya-kibir adalah beberapa penyakit hati yang akan menyebabkan tak enaknya laku kehidupan seseorang di mana pun ia berpijak.
Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa akar dari radikalisme dan terorisme tak semata ditentukan oleh faktor ekonomi, politik maupun sosial. Bisa jadi radikalisme dan terorisme itu lebih berakar pada permasalahan hati. Bukankah al-Ghazali pernah mengandaikan bahwa kalbu adalah laiknya sang perdana menteri dimana anggota-anggota tubuh lainnya hanyalah para serdadunya?
Pada sembah kalbu, R.M. Sindura menyajikan indikasi seseorang yang sudah sampai pada tahap yang tak lagi radikal. “Sarat sareh saniskareng laku” merupakan karakter yang terbentuk karena sembah kalbu ini. Maka dapat diandaikan, ketika seseorang berhujah keagamaan omongan dan segala tingkah-lakunya tak akan membuahkan perkara. Otaknya akan sedemikian diberi ruang sehingga seumpamanya menghakimi berbagai produk yang belum ada di masa nabi dan para sahabatnya, ia tak lupa bahwa tangannya tengah menggenggam salah satu produk yang dihakiminya itu.
Saya kira sampai pada tahap sembah kalbu ini saja ruang bagi radikalitas sudah menyempit dengan sendirinya. Sebab, ketika benar seseorang itu mendasarkan kehidupannya pada al-Qur’an, tentu ia tahu dan tak akan mem-bid’ah-kan praktik sembah kalbu semacam ini (Kahanan: Melongok dari yang Tak Pokok, Heru Harjo Hutomo, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021).
Bukankah konon hanyalah jiwa yang tenteram yang diperkenankanNya pulang dengan ridha dan diridhaiNya? Ketika indikasi moderatisme dalam beragama adalah ketenteraman, bukankah mem-bid’ah-kan, menkafirkan, dan bahkan mempersekusi lyan justru menjauhkan diri dari suasana yang seolah sudah digariskan oleh al-Qur’an?
*) Artikel ini adalah hasil kerja sama alif.id dan Jaringan GUSDURian untuk kampanye #IndonesiaRumahBersama
https://alif.id/read/hs/moderatisme-beragama-dalam-kacamata-sufisme-nusantara-4-b240847p/